Meskipun perselisihan para sejarawan sudah berlangsung lebih dari tiga dekade, konsekuensinya terus membentuk kebijakan historis dan citra diri Jerman hingga hari ini. Tokoh sentralnya adalah Ernst Nolte: dengan esai tentang Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)di mana ia mengajukan pertanyaan apakah “Kepulauan Gulag” lebih otentik daripada Auschwitz, ia berubah dari seorang sarjana yang dihormati menjadi seorang paria di salon.
Namun pendekatan awalnya masih dianggap berpengaruh hingga saat ini, terutama dalam penelitian holisme. Sejarawan dan filsuf ini akan berusia 100 tahun pada 11 Januari, itulah sebabnya Perpustakaan Konservatorium di Berlin mendedikasikan simposium kepadanya pada Jumat lalu.
Melawan slogan negara bangsa
Apa yang menjadikan konflik tahun 1986 menjadi perdebatan besar akan dianalisis Gerrit Duroc. Dosen sejarah modern di Universitas Teknik Braunschweig ini melihat kontroversi Nolte sebagai puncak dari beberapa garis konflik diskursif: pencarian identitas nasional Jerman Barat dan pencarian kekuasaan oleh kaum liberal kiri dan liberal-konservatif. . “Di pihak liberal kiri, hak untuk hidup sebagai negara bangsa Jerman sebagian besar telah ditolak,” kata Duroc.
Intelektual seperti Jürgen Habermas menggambarkan Republik Federal sebagai “demokrasi yang sepenuhnya pasca-nasional” dan berpendapat bahwa Auschwitz harus dianggap sebagai “mitos pendiri Republik Federal”. Di sisi lain, Nolte, yang menentang “lagu indah negara-bangsa Jerman,” mendukung kaum konservatif liberal: “Mereka melihat pemikiran positif tentang sejarah nasional sebagai peluang untuk melestarikan kesadaran kolektif di antara orang Jerman,” tegas sejarawan tersebut.
Dia menggambarkan hasil konflik itu kontradiktif. Kedua kubu mampu meraih kesuksesan: di satu sisi, bangsa ditegaskan sebagai acuan kolektif, namun di sisi lain, sikap kritis terhadap sejarah modern menjadi kewajiban warga negara. Duroc mengatakan perselisihan para sejarawan bukanlah sebuah “pertempuran defensif” yang dilancarkan oleh Partai Demokrat melawan sayap kanan yang tidak demokratis, namun lebih merupakan “debat budaya dan politik di mana kubu liberal kiri menemukan kondisi yang jauh lebih baik daripada yang diklaim di masa lalu.”
Fasisme: Bagi Ernst Nolte, sebuah fenomena sejarah

Horst Müller memiliki pendapat serupa. “Mungkin tidak ada sejarawan di sini yang difitnah seperti ini,” katanya. Mantan presiden Institut Sejarah Kontemporer ini menekankan bahwa dalam konflik sejarawan, hampir semua kaum kiri tidak hanya kehilangan “moral yang baik”, tetapi juga semangat ilmiah. Dia sebelumnya telah mengakui pengaruh “fasisme pada masanya” dalam ceramahnya pada tahun 1963. “Harus dikatakan bahwa banyak buku setelahnya [Nolte] “Mereka muncul dan terinspirasi olehnya dalam satu atau lain cara,” kata Mueller.
Nolte memilih pendekatan komparatif secara konsisten karena dua alasan: baginya, fasisme hanya dapat dipahami sebagai fenomena sejarah dari tahun 1917 hingga Perang Dunia II, dan tahun 1919 (publikasi Manifesto Fasis – catatan editor) adalah tahun penting baginya. ini. Menurut sejarawan tersebut, historisisasi fasisme dengan bantuan kriteria definisi yang tepat memiliki satu tujuan: para peneliti totalitarianisme pada saat itu khawatir bahwa fasisme akan menjadi “istilah populer” yang dipolitisasi oleh kaum kiri.
Dalam penjelasannya mengenai fasisme, Nolte memperkenalkan istilah antropologi. “Apa yang banyak menimbulkan kesalahpahaman dalam studi sejarah adalah konsepnya tentang transendensi,” kata Müller, seraya menambahkan bahwa ia mendefinisikannya sebagai “fenomena trans-politik.” Meskipun fasisme harus dipahami terutama sebagai sebuah fenomena politik, Nolte mengakui bahwa hanya struktur transpolitik yang membuat dampaknya dapat dipahami secara historis: “Dari sini saya kemudian menyimpulkan bagaimana utopia rasis Hitler, dan bentuk-bentuk anti-Semitisme yang mematikan, membuat Kejahatan seperti itu mungkin terjadi melalui kebijakan sosial.” “mental.”
Pelajar, cinta, Cheka, anti komunisme
Nolte sudah membaca tentang kejahatan di masa mudanya. “Membaca semua jenis buku secara intensif dan terkadang sangat intens (…) bisa sangat formatif dalam kasus-kasus tertentu,” kata Hans-Christoph Kraus, seraya mencatat bahwa hal ini juga berlaku untuk Nolte. Profesor sejarah modern di Universitas Passau menambahkan bahwa menurut “kesaksian yang diberikan beberapa kali,” bacaan awal tertentu memicu minat masa kecilnya terhadap perkembangan dan konteks politik saat ini.
Ini adalah novel otobiografi Alya Rachmanova, seorang penulis Rusia yang tinggal di pengasingan di Austria. Bukunya yang paling terkenal, Pelajar, Cinta, Cheka dan Kematian, tidak hanya menyita perhatiannya semasa kanak-kanak tetapi juga dikutip dengan sangat rinci dalam banyak novel ilmiah Nolte, terutama dalam Perang Saudara Eropa tahun 1987. Bagi Krauss, Buku ini menyampaikan sebuah “kesan asli” tentang “kebrutalan yang tidak dapat dipahami” yang ditimbulkan oleh Revolusi Oktober dan setelahnya.
Ernest Nolte sebagai kritikus kolonialisme
Patrick Banners, pada gilirannya, membangun jembatan menuju masa kini. itu telah menang-Wartawan menyinggung apa yang disebut Sengketa Sejarawan 2.0, yang berkisar pada dugaan pengaruh kolonialisme terhadap kejahatan rezim Nazi. Dalam pidatonya kepada para pakar pascakolonial, ia mengajukan pertanyaan: “Mungkinkah mereka meremehkan bahwa memang ada minat dan kesadaran terhadap pertanyaan-pertanyaan kolonial ini pada masa-masa awal Republik Federal?”
Dia sebagian besar mengutip dari buku “Jerman dan Perang Dingin” tahun 1974. Menurut Nolte, setiap negara besar kontemporer yang telah menetapkan tujuan luar biasa memiliki “era Hitler” sendiri dengan “monster” dan korbannya. Dari sudut pandang tersebut, ia antara lain mengkritik Nasserisme di Mesir, rezim Sukarno di Indonesia, Zionisme di Israel, dan bahkan Gaullisme di Prancis. “Klip-klip ini mungkin mempermasalahkan gagasan bahwa Nolte berurusan dengan seorang pembela nasionalis tradisional,” kata Bahner.

Pertemuan yang tidak mungkin terjadi di tempat lain
Pembicara lain memperhatikan sisi filosofis Nolte. Wilko Richter, lulusan Universitas Bielefeld, mempelajari pengaruh filsafat Heidegger terhadap karya sejarawan sebagai bagian dari tesis masternya dan menyerukan pengakuannya sebagai filsuf sejarah. Dia mengacu pada “Eksistensialisme Historis” dari tahun 1998, di mana Nolte menggambarkan beberapa ciri kekuasaan dan rezim sebagai sesuatu yang ontologis dalam pengertian Heidegger. Sejarawan kuno Uwe Walter juga merujuk pada karya tersebut dalam ceramahnya. Perjuangan untuk “keseluruhan sejarah menjadi jelas,” telah tercapai.
Pertemuan selama delapan jam yang berlangsung dalam suasana bersahabat dan terbuka ini juga mendapat pujian dari para pembicara. “Dalam kondisi universitas-universitas Jerman saat ini, tidak mungkin mengadakan acara seperti itu untuk penulis kontroversial seperti Nolte,” kata Kraus sambil berterima kasih kepada penyelenggara.

“Penggemar twitter yang bangga. Introvert. Pecandu alkohol hardcore. Spesialis makanan seumur hidup. Ahli internet.”

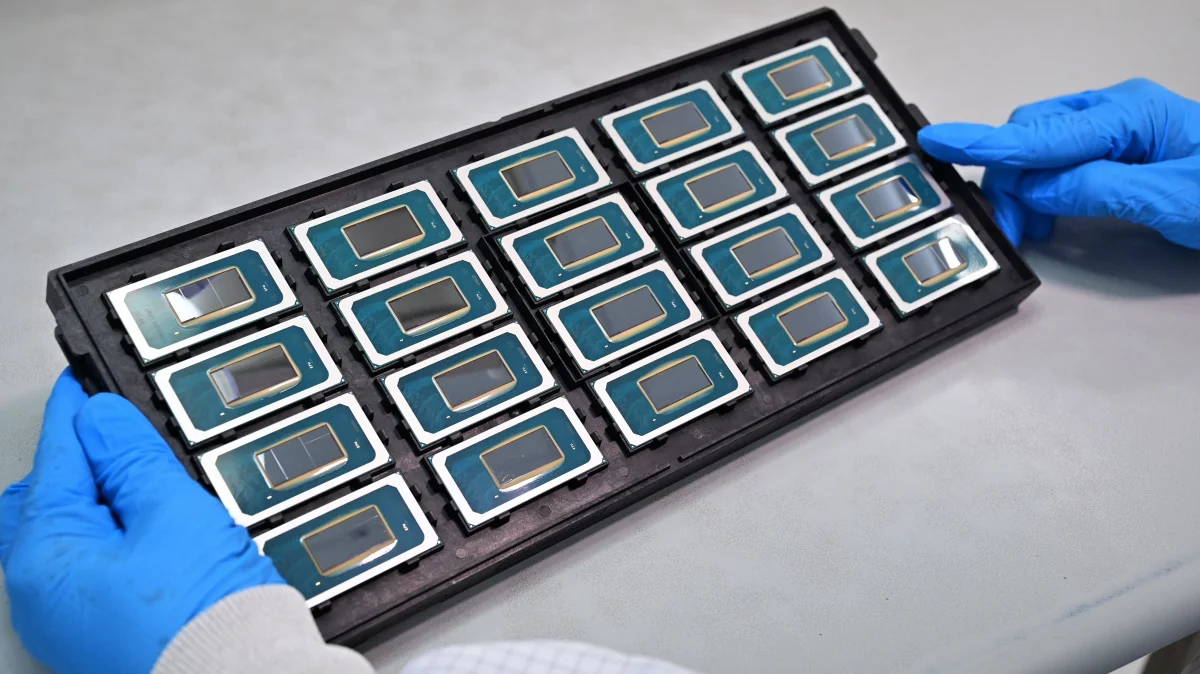




More Stories
Hari pertama Piala Dunia di Singapura dibatalkan karena buruknya udara
Asap mematikan menyelimuti Indonesia – DW – 28 Oktober 2015
Indonesia: Situasi penyandang disabilitas intelektual masih genting