Apakah pengakuan rasisme kolonial mengarah pada penindasan Holocaust? nomor. Refleksi setahun penuh perdebatan sengit. Ditulis oleh Michael Rothberg.
Buku saya Multidirectional Memory diterbitkan dalam terjemahan bahasa Jerman setahun yang lalu, dua belas tahun setelah versi aslinya diterbitkan. Itu diterima dalam versi bahasa Inggris sebagai bagian dari “Fase Tiga” (Astrid Earl) dari Memory Research. Itu tentang memperluas pemahaman tentang memori kolektif yang muncul dari karya berpengaruh pada tahap awal, yang mencakup tokoh utama sosiolog Maurice Halbwachs dan sejarawan Pierre Nora. Alih-alih konsepsi memori yang statis, berbasis bangsa, dan homogen secara budaya yang mendasari proyek “Alternatif Memori” Nora, memori digambarkan dalam fase ketiga ini sebagai dinamis: sebagai transnasional, multikultural, dan multikultural. Buku saya, Multidirectional Memory, yang menelusuri interaksi ingatan Holocaust, kolonialisme, dan perbudakan di ruang transnasional dan menghubungkan orang kulit hitam dan Yahudi, dengan cepat menjadi titik referensi penting dalam diskusi tentang ingatan kolektif.
Sambutan di Jerman benar-benar berbeda. Alih-alih menjadi bagian dari diskusi tentang sifat ingatan, buku itu mengarah ke perdebatan sengit tentang keunikan Holocaust, sifat anti-Semitisme, dan kemungkinan kritik terhadap politik Israel. Kontroversi seputar buku tersebut segera menjadi terkait dengan Membe Affair, yang juga berkaitan dengan Holocaust, anti-Semitisme, dan konflik Israel-Palestina, dan pada gilirannya mengarah pada diskusi tentang hubungan antara genosida Yahudi Eropa, Nazisme, dan kekerasan kolonial. Pada saat yang sama, hubungan antara genosida kolonial Jerman dan Holocaust dihidupkan kembali berdasarkan karya sejarawan Jürgen Zimmerer, paling tidak sehubungan dengan pertanyaan apakah memori Holocaust adalah “memori layar” dari penjajah. Penyimpanan.
Argumentasi oleh A. Dirk Moussa
Dengan semua aspek kontroversial dari konvergensi Jerman di masa lalu dan sekarang, sebuah esai polemik oleh sejarawan Australia yang berbasis di AS A. Dirk Moussa di blog Swiss History of the Present. Di sana Musa mengidentifikasi ciri-ciri penting dari apa yang disebutnya “agama sipil” Jerman yang, menurutnya, menjadi tidak liberal atau bahkan otoriter. Selain itu, ia menghitung pandangan tentang keunikan Holocaust, perbedaan tegas antara anti-Semitisme dan bentuk rasisme lainnya, dan hubungan pendek antara anti-Zionisme dan anti-Semitisme. Setelah artikel Moses melihat debat yang hidup dalam bahasa Inggris, artikel Jerman mengambil debat tersebut, dengan nada yang berubah secara drastis. Renungan Musa, khususnya wacana yang didasarkan pada klasifikasi agama, ditolak mentah-mentah.
Reaksi, paling tidak terhadap konsep memori multiarah dan karya Achilles Mbembe dan Jürgen Zimmerer, tampaknya mengkonfirmasi asumsi Musa tentang poin-poin utama. Seperti yang dia prediksi, tuduhan mencurigakan anti-Semitisme telah menyebar hampir pada tingkat inflasi, misalnya untuk mencemarkan nama baik jurnalis perempuan (Caroline Emki dan Nimi Alhassan) dan yang lebih baru seniman dan lembaga seni (Masyarakat Indonesia Ruangrupa dan Documenta). Tidak ada keraguan bahwa laporan terbaru oleh Amnesty International Inggris yang menggambarkan Israel sebagai sistem apartheid akan memicu lebih banyak kontroversi di Jerman, meskipun kelompok hak asasi manusia di Israel telah menggunakan istilah apartheid. Seseorang dapat secara ilmiah memperdebatkan studi genosida komparatif, teori ras kritis, dan politik Israel, tetapi sebagian besar suara publik di Jerman bermusuhan dan tidak mau terlibat secara serius dalam argumen yang menantang aspek pandangan dominan tentang Holocaust, anti-Semitisme, dan Negara Bagian. Israel.
Daripada membuka kembali pertanyaan tentang keunikan Holocaust – yang ingin ditekankan oleh kelompok terakhir A Crime Without a Name (diedit oleh Saul Friedländer, Dan Diner, Sybille Steinbacher, dan Norbert Frei – lihat juga FR 02/08), saya akan ingin melihat perdebatan ini dari sudut yang berbeda. Jelas dari banyak tanggapan yang menyentuh saraf terletak pada pernyataan bahwa budaya peringatan Holocaust Jerman yang banyak dipuji memiliki kekurangan yang serius, bahkan anti-demokrasi. Klaim seperti itu tampaknya melemahkan upaya untuk menjadikan tanggung jawab atas Holocaust sebagai bagian integral dari identitas Jerman. Kekhawatiran tampaknya adalah bahwa para kritikus “pasca-kolonialisme” akan merusak pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dan dengan demikian bermain di tangan sayap kanan, tetapi dalam konteks ini didasarkan pada serangkaian kesalahpahaman dan terkadang kebingungan yang disengaja.
Perbandingan Holocaust diperiksa
Pertama, penentang metode multi-arah sering mengacaukan sejarah dengan memori. Tentu saja, mereka tidak dapat dipisahkan sepenuhnya, tetapi buku saya dan artikel Musa ditujukan untuk memori budaya, bukan penelitian sejarah. Hal ini tampaknya sulit untuk dipahami oleh beberapa kritikus, sebagaimana dibuktikan oleh kecepatan para jurnalis seperti Thomas Schmid (“Die Welt”) dan Claudius Seidl (FAZ) berpindah dari refleksi saya tentang dinamika ingatan ke argumen historis Zimmer tentang genosida kolonial dan Holocaust.
Contoh terbaru adalah kontribusi Sibel Steinbacher untuk A Crime Without a Name, di mana saya mencoba untuk melawan pandangan saya dan Zimmerer bahwa perbandingan dengan Holocaust tunduk pada pengawasan ketat di depan umum, mencatat bahwa penelitian genosida komparatif telah lama menjadi penelitian yang mapan. ladang—seolah-olah Musa dan para tukang kayu perlu mengingatkan.
Ya, perbandingan diperbolehkan, tetapi di pusat-pusat wacana publik paling berpengaruh di Jerman – tidak seperti di dunia akademis – satu-satunya hasil yang dapat diterima dari perbandingan semacam itu adalah pembaruan sifat unik Holocaust. Penyangkalan kesamaan ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk terlibat secara serius dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kerangka sejarah yang lebih besar, termasuk kolonialisme dan konstruksi etnis trans-Eropa, yang sama sekali tidak unik bagi Musa dan Zimmerer.
Kedua, banyak kritikus terus mengajukan jenis logika zero-sum, apa yang saya sebut “memori kompetitif,” bahkan ketika mereka mengklaim bahwa mereka yang mempromosikan pendekatan relasional bermusuhan dan bermusuhan. Sebaliknya, argumen buku saya adalah untuk mengasumsikan bahwa memori tidak beroperasi sesuai dengan logika permainan zero-sum. Tunjukkan bahwa bahkan konflik memori menghasilkan lebih banyak memori, bukan lebih sedikit. Memori Multidirectional menawarkan pandangan yang berpotensi toleran berdasarkan premis bahwa budaya memori terjalin lebih erat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Namun, contoh mempertahankan logika zero-sum dapat ditemukan di artikel Dan Diner yang menyimpulkan “A Crime Without a Name”.
Berdasarkan argumennya tentang singularitas “anti-rasional” dari Holocaust, referensi Diner terhadap anti-rasisme gerakan Black Lives Matter menunjukkan bahwa mereka yang meminta perhatian pada keyakinan rasis dan kolonial Winston Churchill mau tidak mau melakukannya sebagai memori Holocaust dirusak. Dia menulis: “Sekarang Churchill, sebagai tokoh abad kesembilan belas, seperti orang-orang sezaman dan rekan-rekannya, bukannya tanpa sikap rasis. Tetapi jika hanya itu yang tersisa untuk Churchill, maka – maka kesimpulan yang sudah dekat – Hitler harus dihapus dari memori sejarah.” Kesimpulan seperti itu diperlukan Hanya jika seseorang mengikuti logika zero-sum, yang berarti bahwa pengakuan apa pun terhadap kolonialisme kecuali rasisme mengarah pada pengurangan otomatis, jika bukan penindasan total, Holocaust.
Kebingungan antara sejarah dan ingatan serta pendekatan zero-sum terhadap budaya ingatan menyatu dalam ketidakmampuan untuk melihat masa kini dengan mata baru. Meskipun Kejahatan Tanpa Nama dimulai dengan peringatan Jürgen Habermas untuk tidak membekukan budaya zikir bangsa, banyak volume yang berkontribusi terhadapnya. Dengan demikian, kebutuhan akan narasi komparatif dari Holocaust dan konsekuensinya menjadi jelas di mana-mana dalam masyarakat saat ini dan dalam perdebatan itu sendiri. Sementara suara-suara berpengaruh mencoba memisahkan anti-Semitisme dari hubungan apa pun dengan bentuk rasisme lainnya, ekstremis sayap kanan suka menargetkan orang Yahudi dan minoritas lainnya, seperti yang dijelaskan oleh serangan bermotivasi rasial di Halle dan Hanau.
Ide-ide penting tentang gerakan sayap kanan yang menyebarkan ideologi supremasi kulit putih, khususnya dari memori Holocaust dan Holocaust, harus muncul. Namun, pembatasan yang diberlakukan sendiri yang tampaknya berlaku untuk istilah anti-Semitisme dan rasisme membuat sulit untuk memahami apa yang terjadi di Jerman saat ini.
Penolakan untuk mengakui Holocaust dan kedekatannya dengan kolonialisme mendistorsi pemahaman kita tentang sejarah dan ingatan. Para sarjana akan terus memperdebatkan hubungan yang tepat antara penjajahan Jerman dan genosida Yahudi Nazi, tetapi semakin banyak sejarawan, setidaknya di luar Jerman, sekarang mengakui bahwa Holocaust terjadi dalam konteks upaya Nazi untuk menjajah Timur. Eropa dan Hitler jelas terinspirasi oleh Kerajaan Inggris dan ekspansi Barat di Amerika Serikat – belum lagi hukum rasial Amerika. Dalam koleksi The Holocaust and North Africa dan buku sumber Wartime North African yang sangat dinanti, rekan Omar Bohm dan Sarah Stein mengeksplorasi persimpangan kolonialisme, fasisme, dan Nazisme di Afrika Utara—perspektif yang membuka pendekatan baru terhadap penelitian Holocaust. Dalam ranah zikir, pembahasan akibat kolonialisme tidak lepas dari pembahasan warisan Holocaust setidaknya karena dua alasan. Di sisi lain, karena mengikuti Holocaust telah menjadi titik acuan instan di seluruh dunia untuk memikirkan berbagai bentuk kekerasan politik; Kedua, karena kaum intelektual Yahudi, kulit hitam, dan lainnya sejak kebangkitan Nazisme selalu memandang pasangan ini sebagai pusat pemahaman sejarah modernitas.
Konvergensi beragam perdebatan tentang kolonialisme, anti-Semitisme, Israel, dan Holocaust itu sendiri merupakan bukti pluralitas tren ingatan dan keterikatan sejarah. Menyebutkan singularitas historis Holocaust tidak akan menghapus keterikatan ini, melainkan akan membuat diskusi di masa depan lebih kasar dan kurang bernuansa. Itu juga akan memperkuat hierarki korban, bahkan jika para kritikus menyangkalnya. Sebaliknya, metode perbandingan akan memungkinkan kita menemukan jalan kita melalui konvergensi dan perbedaan dalam warisan sejarah yang menyakitkan tanpa memihak satu cerita di atas yang lain. Budaya zikir Jerman pada 1980-an menunjukkan potensi kritik diri untuk berdamai dengan masa lalu dengan cara yang patut dicontoh. Sementara itu, dimensi kritis-diri ini telah menguap secara signifikan dan digantikan oleh arus yang tidak liberal. Namun, pada akhirnya, pendekatan multi-arah menjanjikan untuk menghidupkan kembali ingatan yang diperoleh dengan susah payah dari budaya Jerman dalam masyarakat yang semakin pluralistik dan kompleks.
Michael Rothbergseorang sarjana sastra Amerika, adalah Ketua Samuel Goetz dalam Studi Holocaust di Los Angeles.

“Penggemar twitter yang bangga. Introvert. Pecandu alkohol hardcore. Spesialis makanan seumur hidup. Ahli internet.”

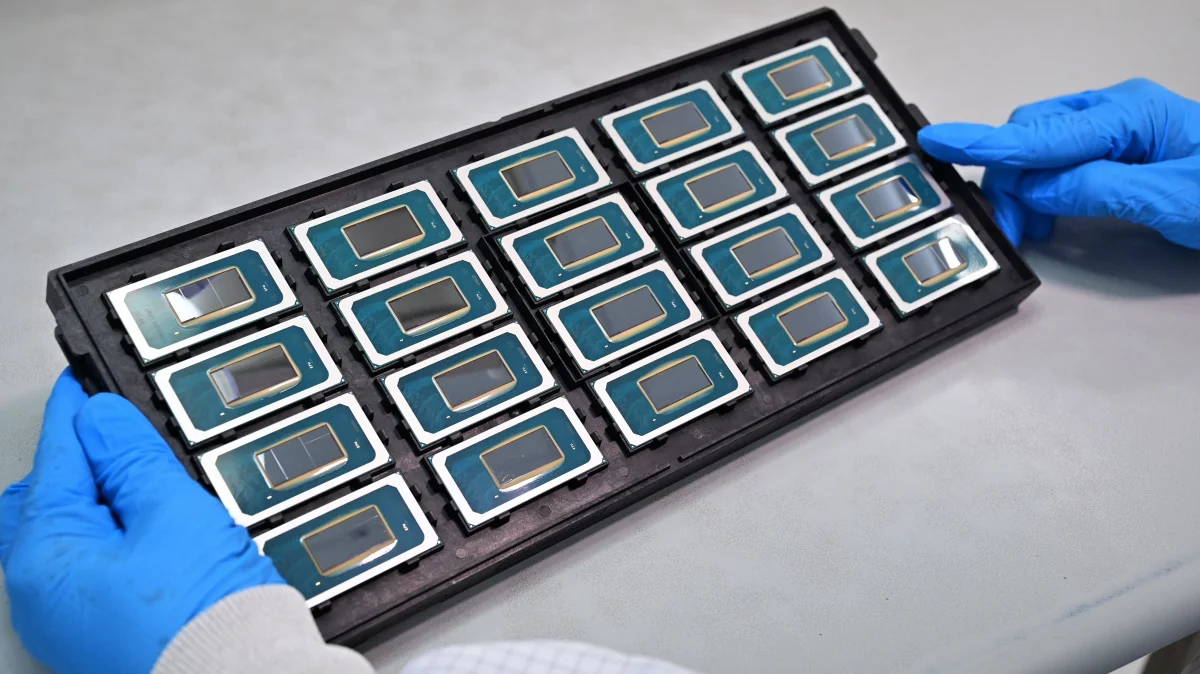




More Stories
Hari pertama Piala Dunia di Singapura dibatalkan karena buruknya udara
Asap mematikan menyelimuti Indonesia – DW – 28 Oktober 2015
Indonesia: Situasi penyandang disabilitas intelektual masih genting