Indonesia menyaksikan salah satu kekerasan anti-komunis paling berdarah di abad ke-20. Setelah kudeta militer pada tahun 1965, perburuan terhadap komunis terjadi, menewaskan sekitar satu juta orang hanya dalam beberapa bulan. Film Joshua Oppenheimer tahun 2012 “The Act of Killing” menangkap pembantaian tersebut dalam gambar yang mengerikan. Oppenheimer meminta para pembunuh kemarin, yang masih tidak dianiaya hingga hari ini, untuk melakukan kembali kejahatan mereka. Kegembiraan yang ditunjukkan para penjahat dalam film tersebut dengan memasang kawat di leher boneka atau mencungkil mata mereka hampir sama sulitnya dengan tidak adanya penyangkalan dan rasa malu yang diungkapkan di dalamnya.
Seperti yang terjadi di Jerman setelah tahun 1945
Namun propaganda resmi yang mengubah korban menjadi monster sadis, dan dengan demikian berupaya untuk melegitimasi pemusnahan mereka, tampaknya masih berdampak di Indonesia hingga hari ini – bahkan tujuh belas tahun setelah berakhirnya rezim Suharto. Namun, konfrontasi dengan sejarah yang keras mengalami kemajuan yang lambat. Inilah kesimpulan menyedihkan yang dicapai oleh penerjemah Peter Sterngel, yang sudah lama tinggal di Indonesia: “Tidak ada keterbukaan langsung. Selalu ada kalangan yang sebenarnya tidak menginginkannya. Hal yang sama terjadi di Jerman setelah tahun 1945 “Bukan seperti itu.
Film lanjutan Oppenheimer, The Look of Silence, yang menampilkan para korban berbicara dengan cara yang pedih, telah dilarang ditayangkan. Sementara itu, Museum Pengkhianatan Komunis yang dibangun di ibu kota, Jakarta, pada tahun 1990, tetap populer. Dalam sebuah pameran yang aneh, komunis digambarkan sebagai binatang buas yang merusak dalam foto dan pemandangan militer.
Sastra Indonesia selalu memperhadapkan pandangan resmi tentang sejarah dengan sudut pandang yang berbeda dan kontras. Komposer modern paling penting di negara ini, Pramoedya Ananta Toer, yang beberapa kali dianggap sebagai nominasi Hadiah Nobel sebelum kematiannya pada tahun 2006, melakukan hal yang sama dalam otobiografinya A Silent Song of a Dumb – dalam situasi yang paling sulit. Namun baru setelah Suharto mengundurkan diri secara paksa pada tahun 1998, peristiwa-peristiwa mengejutkan tersebut menjadi lebih terbuka dan didiskusikan secara empatik.
Wanita mendapat pencerahan
Penulis pertama yang melakukan hal ini adalah Ayu Utami. Novelnya “Saman” yang terbit pada tahun 1998 melanggar banyak pantangan dan membuatnya terkenal di Indonesia. “Saman” dan sekuelnya “LaRong” kini tersedia dalam bahasa Jerman. Bagi Ayo Utami, terlibat dalam sejarah tidak pernah kehilangan urgensinya. “Seorang penulis tidak boleh ragu untuk mengingatkan pembacanya tentang hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu,” ujarnya. “Kita harus menghadapi apa yang terjadi agar hal itu tidak terjadi lagi.”
Io Utami yang pemberani diikuti oleh penulis lain, kebanyakan perempuan. Novel-novel penuh wawasan karya Leila Chowdhury dan Lakshmi Pamunjak, Bulang (Kembali ke Jakarta) dan All the Reds, kini telah diterbitkan dalam bahasa Jerman, keduanya membahas warisan berat dari pembunuhan massal. Leila Chowdhury khususnya, yang juga suka menggunakan kata-kata yang jelas sebagai jurnalis, sangat kritis terhadap kebijakan zikir pemerintah saat ini: “Perjalanan kita masih panjang. Pemerintah belum benar-benar menerima apa yang terjadi. Mereka menyangkal atau bertahan. diam.” Mengenai apa yang terjadi, orang-orang ini bisa dibilang acuh tak acuh terhadap hak asasi manusia, dan hingga hari ini, Anda dapat yakin bahwa sebagian besar masyarakat telah dicuci otak selama 32 tahun.
Sastra yang berkomitmen
Para penulis Indonesia menulis menentang indoktrinasi ini tanpa memperlambat semangat mereka. Dengan caranya sendiri, setiap kisah mengenai pembantaian yang terjadi hampir lima puluh tahun yang lalu memberikan wawasan terperinci mengenai jiwa suatu negara dalam masa transisi, yang disertai dengan trauma mendalam yang belum terselesaikan. Ini adalah upaya sastra yang berhasil untuk membicarakan apa yang telah lama dirahasiakan dan pada saat yang sama mempertanyakan versi resmi dari peristiwa masa lalu.
Bagi Lakshmi Pamontjak, menulis adalah sebuah proses pembelajaran: “Saat mengerjakan novel ini, saya menyadari sesuatu: seorang penulis yang memutuskan untuk menceritakan masa lalu seperti yang saya lakukan, mempunyai tanggung jawab, bahkan kewajiban, untuk mencoba mempengaruhi masa lalu. cara orang berpikir, untuk mempengaruhi ide-ide mereka—dengan cara apa pun.” Seorang novelis debut tidak hidup dengan asumsi bahwa sebuah buku dapat mengubah dunia. Namun, dia yakin: “Individu bisa dijangkau, dan itu berarti banyak. Jika Anda kehilangan kepercayaan pada kekuatan buku untuk melakukan hal itu, mengapa Anda harus menjadi penulis?”

“Penyelenggara. Ahli media sosial. Komunikator umum. Sarjana bacon. Pelopor budaya pop yang bangga.”

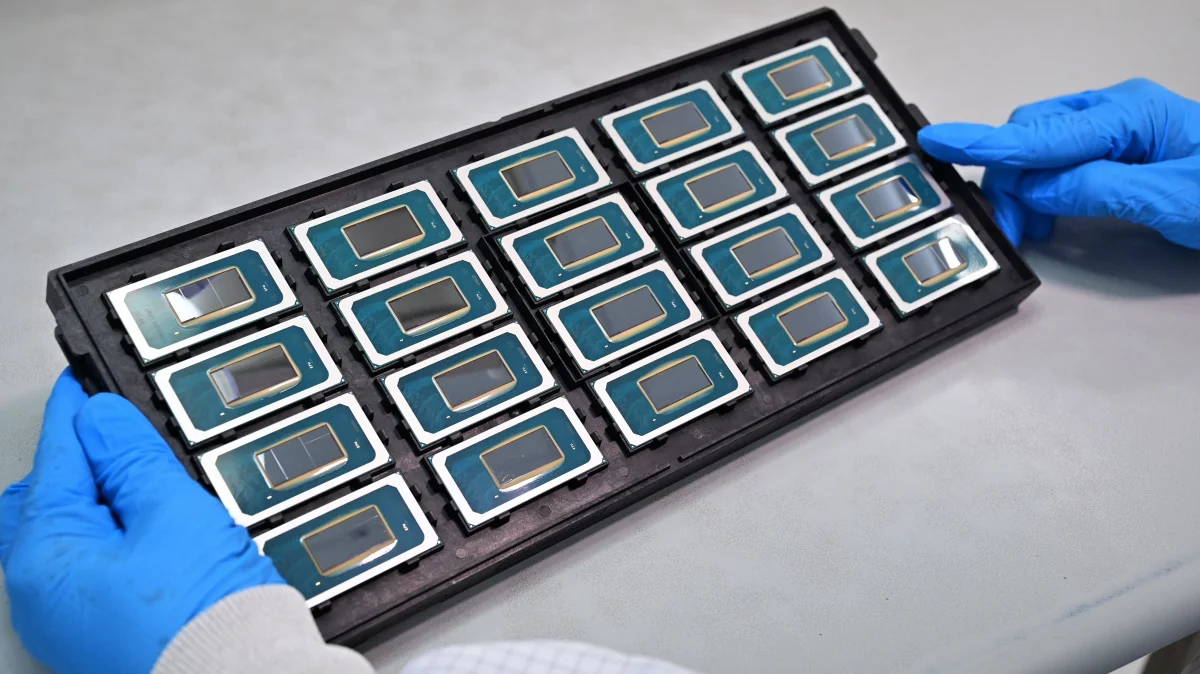




More Stories
Pekan Film Indonesia di FNCC – Allgemeine Zeitung
Seorang binaragawan meninggal setelah mengalami kecelakaan menggunakan dumbel seberat 210 kg
Kejutan badai di Sylt: pelampung cuaca raksasa tersapu ombak