Bayangkan beberapa pembunuh Nazi, yang tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, tidak hanya membual tentang mereka di depan kamera, tetapi juga secara tidak profesional memerankan kembali kejahatan mereka dalam semacam film fiksi kamp konsentrasi. Di sela-sela itu, mereka menyampaikan rincian sel penyiksaan dan kamar gas, tersenyum malu-malu namun tidak pernah terkejut. mustahil? mungkin ya. Intinya, inilah yang terjadi dalam The Act of Killing. “Saya dianiaya oleh orang-orang yang saya bunuh dengan kabel,” keluh salah satu dari mereka. Ini cukup bagi mantan algojo lainnya untuk merekomendasikan menemui ahli saraf. Jelas sekali, pembunuh massal tidak memiliki kehidupan yang mudah; Dan terkadang Anda merasa kasihan pada orang-orang yang secara brutal menyiksa ratusan orang seperti mereka hingga meninggal. Jika para algojo kehilangan kesabaran setelah berjam-jam melakukan penyiksaan yang melelahkan, beberapa pukulan dengan tongkat baseball atau cincin kawat sudah cukup untuk mengakhiri masalah tersebut. Atau otak mereka diledakkan dari tengkoraknya dengan senjata kaliber berat. Bagaimanapun, mereka adalah komunis, sayap kiri, atau Tiongkok; Saat itu masyarakat tidak menganggapnya serius ketika terjadi penganiayaan terhadap komunis yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno atas dorongan Amerika Serikat. Periode yang berlangsung hingga tahun 1980-an ini digambarkan dengan gamblang oleh Peter Weir dalam bukunya A Year in Hell (fd 24 024); Selain anti komunis, ada juga rasisme anti China. Dalam film dokumenter Joshua Oppenheimer “The Act of Killing”, yang menerima banyak penghargaan dan penghargaan pra-rilis, era ini direkonstruksi dengan cara yang sangat orisinal. Kesan mendasar dan ambigu dari filmnya, yang memecah belah penonton, sudah tercermin dalam judulnya: kata “act” dalam bahasa Inggris tidak hanya berarti “act” atau “act”, tetapi juga berarti tindakan seorang aktor dan dengan demikian menunjukkan sebuah aksi. Tema lucu yang hadir dalam konteks pembunuhan massal yang dilakukan oleh paramiliter dan milisi sayap kanan dalam film ini terkesan remeh. Permainan ini dimainkan di sini sepanjang waktu. Hampir seluruh gambar dalam film tersebut berasal dari masa kini. Oppenheimer mencari pembunuh yang bersedia memberikan informasi dan dengan kebanggaan yang tidak terselubung. Mereka segera sepakat untuk memerankan kembali tindakan mereka dalam bentuk panutan sinematik yang relevan (dari Bollywood hingga “The Godfather”). Selama “peragaan ulang” semacam ini beberapa dari mereka mulai berpikir. “Tindakan membunuh” meresahkan dan menakutkan, salah satunya karena hal-hal sepele yang dialami seseorang selama dua jam. Anda melihat orang-orang mengenakan kemeja Hawaii yang hambar dan tinggal di apartemen sederhana, dan Anda mendengar alasan-alasan yang lazim dari para antek dan pengikut kediktatoran (“Itu salah, tapi kami harus melakukannya”), disampaikan dengan cara yang arogan dan mementingkan diri sendiri. nada yang membesar-besarkan. Secara formal, elemen teatrikal mendominasi, dan Anda melihat orang-orang bermain, berakting, dan memerankan kembali peran. Sifat film yang kuat dan nyata, seperti yang dicatat oleh produser Werner Herzog dalam materi pers, terutama terletak pada fakta di balik gambar tersebut, bukan pada gambar itu sendiri. Banyak sekali perbincangan dalam film ini, bahkan terkadang dibicarakan; Film dan penontonnya harus menempuh perjalanan jauh agar momen katarsis bisa terjadi. Pembunuh dipandang sebagai “manusia”. Tidak ada keraguan bahwa mereka memang benar. Fakta bahwa Anda masih harus menekankan hal ini adalah inti permasalahannya. Pasalnya, fakta bahwa para pembunuhnya masih manusia tidak terbukti dengan sendirinya mengingat kebrutalan perbuatan mereka. Kejahatan yang mereka lakukan adalah kebrutalan dan kesulitan hidup sehari-hari yang luar biasa, kesadisan yang membedakan mereka dan membedakan mereka dari orang lain, bukan fakta bahwa mereka mempunyai keluarga atau baik terhadap cucu-cucu mereka. Mimpi buruk yang menyiksanya, dan rasa jijik yang menguasainya karena masa lalunya, sungguh disayangkan. Akan tetapi, sudah merupakan sisa dari sentimen yang ketinggalan jaman jika kita melihat bahwa para korban akan menukar masalah tersebut dengan apa yang telah menimpa mereka di tangan tuan-tuan tua yang baik hati itu. 40 tahun kemudian, mereka kini sedikit terkejut dan menemukan juru bicara Joshua Oppenheimer, yang juga menyelubungi ingatan mereka. Di Indonesia, film ini mungkin mewakili terobosan yang telah lama ditunggu-tunggu. Bagi pemirsa di Eropa, “The Act of Killing” hanyalah salah satu dari banyak film dokumenter tentang pembantaian dan genosida yang, alih-alih menyajikan fakta secara langsung, mereka mencoba menggunakan pendekatan “di luar kotak” yang halus, namun pada akhirnya melelahkan. . Penghambatan dan spiritualisasi. Hal ini dapat dibenarkan dengan fakta bahwa akses langsung tidak mungkin dilakukan karena kurangnya bahan. Itu hasil yang salah. Sebab, sejujurnya, penonton tidak peduli apakah seorang pembunuh massal yang tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya terkadang merasa tidak enak atau bahkan muntah-muntah di akhir; Sebaliknya, perasaan ini seharusnya muncul dalam diri penonton. Namun ketertarikan Oppenheimer memastikan bahwa penonton selalu berada pada sisi yang aman.

“Penyelenggara. Ahli media sosial. Komunikator umum. Sarjana bacon. Pelopor budaya pop yang bangga.”

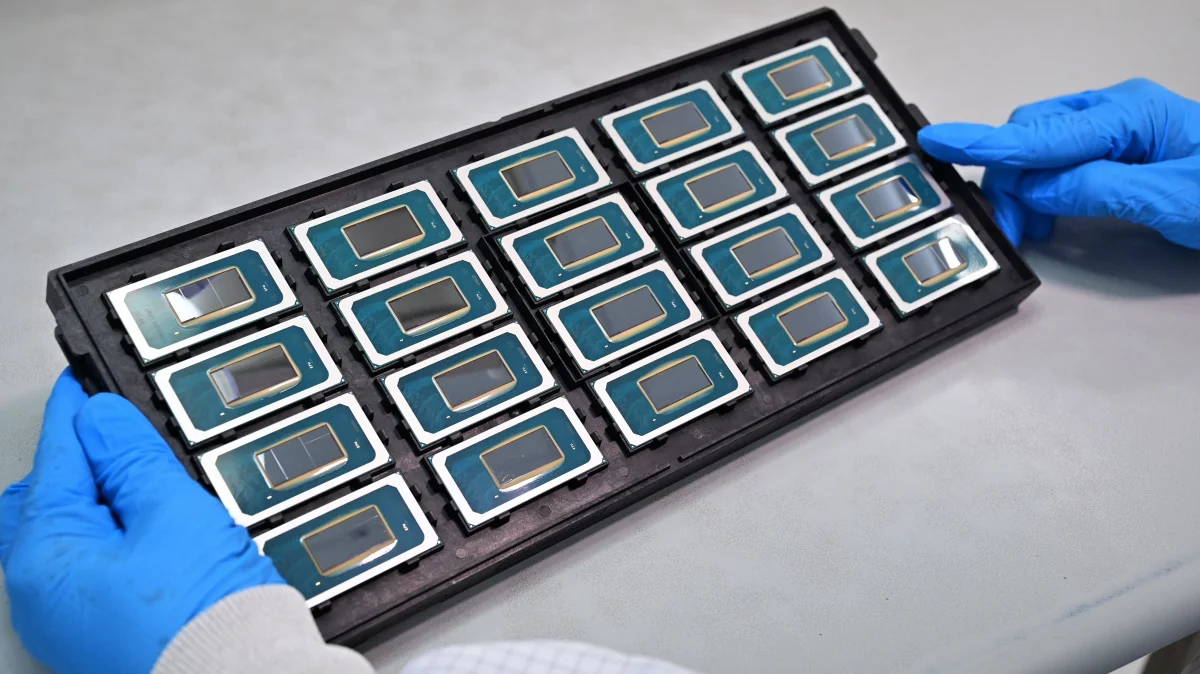



More Stories
Pekan Film Indonesia di FNCC – Allgemeine Zeitung
Seorang binaragawan meninggal setelah mengalami kecelakaan menggunakan dumbel seberat 210 kg
Kejutan badai di Sylt: pelampung cuaca raksasa tersapu ombak