Pulau Impian Bali. Enam juta turis setiap tahun. Pantai, kesenangan berselancar dan budaya. Itu begitu. Tapi kemudian Covid datang. Dan pulau impian telah berubah.
“Lumayan kosong. Saya takut banget. Sore-sore. Sore jam 3.00 pagi saya takut karena tidak ada orang di jalanan. Kosong. Saya melihat ke kiri dan ke kanan, takut ada orang yang lewat. dirampok di jalan-jalan kosong.” Itu penuh sesak di sana. “Semuanya tutup hari ini,” kata Wayan, yang menyewakan kursi.
“Pucat, aku akan pergi, oke?
Jauh dari pantaimu yang seharusnya begitu indah
Tapi dikelilingi oleh hotel-hotel raksasa.”
Band Bali Nosstress menyanyikan lagu tentang pulau ibu mereka, lagu tersebut berasal dari tahun 2017. Selama pandemi, lagu tersebut terdengar seperti soundtrack. Arus turis terhenti. Di hotel, ada banyak ruang. pantai-pantai yang sepi. Pro dan kontra dari industri pariwisata yang luas telah berada di bawah kaca pembesar dalam beberapa tahun terakhir.
Kelemahan menjadi pulau surga
Pada awal abad terakhir – masih di bawah kekuasaan kolonial Belanda – Bali mencapai ketenaran internasional sebagai pulau surga. Sejak 1970-an di bawah kediktatoran Suharto, ia ditakdirkan untuk menjadi pelopor luar biasa ekonomi modern. Bagi sopir taksi Saferius, daya pikat Bali sudah jelas:
“Di mata dunia, Bali memang luar biasa. Budayanya, masyarakatnya ramah, perilakunya ramah. Semua orang yang datang ke sini senang karena begitu indah. Aturannya sedikit. Hanya turis yang bisa naik sepeda. Tolong tidak ada masalah. Yang terbaik, kan?”

Dengan merebaknya wabah Covid-19, banyak wisatawan yang terburu-buru meninggalkan Bali pada Maret 2020 dan tidak lagi dalam skala tersebut hingga sekarang.© imago images / INA Photo Agency / Mohamed Rifki Riyanto
Sebelum pandemi, jumlah wisatawan yang mendarat di pulau itu setiap tahun lebih banyak daripada jumlah wisatawan Bali yang menetap di sana. Pantai Kuta terutama menarik banyak orang dari Australia, seperti penembak Asia. Bali sendiri menyuntikkan beberapa miliar dolar AS ke perbendaharaan nasional setiap tahun. Pulau ini sepenuhnya ditujukan untuk alien yang mencari matahari. Aib, kata Fenty Liliani, seorang jurnalis dan karena itu bagian dari kelas menengah.
“Banyak dari mereka yang mabuk, dan mereka tidak peduli dengan sekitarnya. Beberapa bahkan berjalan telanjang. Ini sebenarnya sangat lucu bagi kita semua. Hei! Turis telanjang!…Tapi mereka juga sangat sensitif. Mereka mengklaim kami menyembah mereka. Kami semua hanya ingin menikmati pulau itu. Mengapa?” Turis bisa menikmatinya tapi kami tidak bisa? Dan entah kenapa selalu karena kami tidak punya cukup uang.”
Bali bagi wisatawan. Dan hanya turis. Itu begitu. TAPI: Pandemi menyapu kompleks hotel yang penuh sesak di Selatan. Ini adalah hal baru bagi penduduk setempat.
Turis sekarang datang dari Indonesia
“Karena Covid, industri pariwisata harus belajar menghargai kita juga. Dari mana mereka mendapatkan uang? Tidak ada turis di sana. Mau tidak mau, mereka harus memberi makan penduduk setempat. Itu bagus untuk saya. untuk mengalaminya juga. Saya ingin pergi ke tempat-tempat istimewa. Hanya Covid yang memungkinkan ini bagi saya! Pengalaman hotel yang luar biasa – wow, akhirnya terjangkau! Begitulah rasanya menjadi turis. Itulah poin plus dari epidemi, ” kata Fenty Lilliani.
Namun industri pariwisata juga mempekerjakan sebagian besar penduduk Bali dan imigran Indonesia. Ketika arus wisatawan mengering, banyak yang kehilangan pekerjaan; Mereka tiba-tiba mampu membawa pulang hanya sebagian kecil dari pendapatan mereka sebelumnya.
“Saya mencari pekerjaan di sana-sini, dan saya pergi ke mana-mana. Saya menghabiskan uang saya untuk bensin. Anda masih tidak dapat menemukan pekerjaan,” kata Wayan, perusahaan persewaan kursi santai.
Banyak warga Bali yang merasakan hal yang sama dengan perusahaan rental kursi berjemur Wayan.
Tidak ada turis, tidak ada pekerjaan, tidak ada makanan
“Kalau pulang, anak saya sering bilang: Ayah, kita belum makan. Baru kemarin lagi. Sorenya saya tutup kursi malas di sini. Lalu anak saya berkata: Ayah, hari ini ada turis di pantai? Saya bertanya mengapa. Kami belum makan Terutama di benteng paket wisata di pantai, pekerjaan menjadi langka – fasilitas terganggu karena staf belum dibayar untuk menjaga mereka tetap dalam kondisi baik. ”
Banyak yang telah kembali ke desa tempat keluarga mereka tinggal, kata seorang manajer hotel.
“Hidup di kota sebenarnya lebih sulit daripada di pedesaan. Semuanya ada di desa. Tidak perlu membayar sewa atau membeli makanan. Semuanya ada di desa. Anda bisa mencari makanan di sana. Karena kerja di desa tidak berhenti di situ, seperti bercocok tanam dan bercocok tanam sayur-sayuran. Bisnisnya menguntungkan di sana.”
Sebagian besar orang Bali yang bekerja di hotel dan restoran di pusat pariwisata pulau ini berasal dari daerah pedesaan di pulau itu. Mereka memiliki keluarga di sana dan dukungan di komunitas desa. Di sana mereka bisa tinggal. Wayan, yang menyewakan kursi berjemur, juga mencoba untuk mendapatkan pijakan sebagai petani.
Kembali ke desa
“Ada pekerjaan. Tapi penghasilannya tidak cukup. Kadang hanya cukup untuk sebulan. Saya tidak bisa menutupi biaya operasi dengan itu. Usaha itu tidak sepadan. Jadi saya bukan petani lama. Hanya sekitar setengah tahun. Setelah itu monyet-monyet dimusnahkan Dan tikus-tikus mencuri segalanya dari hasil panen saya. Tidak ada yang bisa melawan epidemi. Semuanya berserakan. Bukan hanya orang-orang yang terancam oleh Covid. Kami semua ngeri.”
Situasi di dalam ruangan juga tegang, di dekat hot spot yoga di Ubud. Makan, berdoa, cinta – itulah tujuan wisatawan individu datang. Nyata!” Bali. Teras sawah – hijau tak berujung.
Jadi Ibo Wayan dan keluarganya membangun rumah liburan di ladang mereka. Ini harus menjadi investasi untuk masa depan. Sekarang mereka duduk di utang rumah kosong. Anda tidak dapat menanam apa pun di ladang yang dibangun, dan Anda tidak dapat memanen apa pun.
“Saya takut! Kami harus membayar pinjaman setiap bulan dan makan juga. Dari mana saya mendapatkan uang? Itu membuat stres. Sewa vila turun. Kami memiliki setidaknya satu turis yang tinggal di rumah kami. Dia bilang dia tidak punya uang . Dia ingin membayar lebih sedikit. Dia berkata Jika tidak, dia akan keluar. Saya takut—dari mana lagi saya akan mendapatkan uangnya? Jadi saya memberikannya setengah harga kepadanya.”
Tidak ada uang untuk makan
Keluarganya menyebut diri mereka Keluarga Bahagia. Terlepas dari segalanya, mereka lebih baik daripada penduduk lain di desa mereka selama pandemi.
“Saya masih bersyukur. Kita bisa bayar bank. Paling tidak beli beras dan sayur. Saya bersyukur. Selama dua tahun kami hidup sehat, rukun. Kakak ipar saya sangat miskin. Dia tidak punya ayah, ibunya tidak bisa bekerja. Sebelum Covid dia bekerja dan kemudian sedih. Di mana dia harus bekerja? Ketika saya membeli 20 kilogram beras, kami membaginya. Agar dia bisa hidup.
Inti dari pariwisata massal. Bentuk kartu pos seperti sawah terasering berubah menjadi semen abu-abu. Selain pura dan pantai yang luas, pemandangan sawah selalu menjadi penyebab utama keramaian di sekitar Bali.

Sawah terasering, seperti yang ditanam sebelum pandemi, sekarang kekurangan budidaya dasar. © imago / perspektif / l. Schulz
Bali memiliki semakin sedikit ruang untuk bekerja di pertanian. LSM lokal juga telah memantau penindasan ini selama beberapa waktu.
“Bagaimana orang bisa kelaparan? Indonesia seharusnya negara agraris. Tanahnya subur dan kita bisa menanam apa saja. Kenapa banyak yang kelaparan?”
Pandemi bisa menjadi kemunduran.
Pemerintah melewatkan banyak momen penting yang bisa memperbaiki situasi. Misalnya, ketika pariwisata terhenti selama pandemi, banyak yang kembali ke desa untuk bekerja sebagai petani. Itu tidak digunakan untuk mengubah kebijakan, seperti, “Oke, mari kita bertani!” Mereka hanya berkata, “Pertanian tumbuh lagi.” Tapi tidak ada yang dilakukan seperti, ‘Jika itu masalahnya, mari kita ubah peraturan. Kemudian kita lebih melindungi pertanian, membuatnya lebih adil. Membuat lebih banyak lahan tersedia.’ Sebaliknya, ketika para turis kembali, orang-orang kembali ke kota.
Tidak ada pelajaran dari epidemi?
Geylang bekerja dengan organisasi lingkungan lokal. Dia juga merupakan anggota pendiri kelompok punk kolektif yang mendukung protes lokal terhadap pariwisata massal.
“Kami ingin menyoroti masalahnya. Kami, orang-orang, harus makan. Dan lahan pertanian terancam hilang? Mungkinkah ada krisis lain. Pandemi atau perang lain, misalnya. Itu mungkin terjadi.”
Di masa pandemi, jemaah menyelenggarakan bank makanan bagi mereka yang pendapatannya anjlok. “Punk Pangan” – diterjemahkan menjadi “Punk Food” – adalah nama kampanye mingguan.
“Waktu pertama kita bagi-bagi makanan banyak yang datang. Banyak yang membutuhkan, ramai sekali. Bahkan harus dibubarkan oleh polisi. Sungguh miris. Seharusnya dia tidak datang ke situ. Seharusnya mereka membantu menjaga jarak. diantara mereka “.
Orang-orang ingin menjaga jarak, tetapi mungkin mereka sangat membutuhkan makanan sehingga mereka memaksa. Kami berkata, “Tolong perhatikan!” , tetapi mereka berkerumun, “Tolong, saya!”.
Krisis telah memperkuat solidaritas
Banyak penduduk Bali hanya selamat dari epidemi karena ada begitu banyak solidaritas di antara penduduk. Mereka yang dapat berpartisipasi.
Bagi Geylang, pandemi benar-benar mengekspos ketergantungan pulau itu pada pariwisata.
“Bagi kami, evil food bukanlah acara amal. Ini adalah solidaritas. Kami tidak hanya bertukar sayuran, tetapi kami juga berbagi pandangan tentang situasi sosial politik dan politik krisis pangan.”
Turis perlahan kembali ke Bali. Apa yang akan bertahan pada hasil epidemi? Apakah putus asa berharap bahwa sesuatu dapat berubah di pulau itu dalam jangka panjang? Geylang ingin agar penduduk tidak terlalu bergantung pada pariwisata. Mereka dapat mempertimbangkan pro dan kontra dari pariwisata.
“Ini tentang memikirkan kembali. Hal terpenting yang sekarang ditanyakan oleh penduduk adalah: Mengapa krisis seperti itu bisa terjadi sama sekali? Ada yang salah di sana. Sikap kritis ini penting agar kita dapat melanjutkan. Hanya jika ini terus berlanjut, bisa sesuatu yang benar-benar berubah dalam situasi sosial dan politik.

“Penggemar twitter yang bangga. Introvert. Pecandu alkohol hardcore. Spesialis makanan seumur hidup. Ahli internet.”

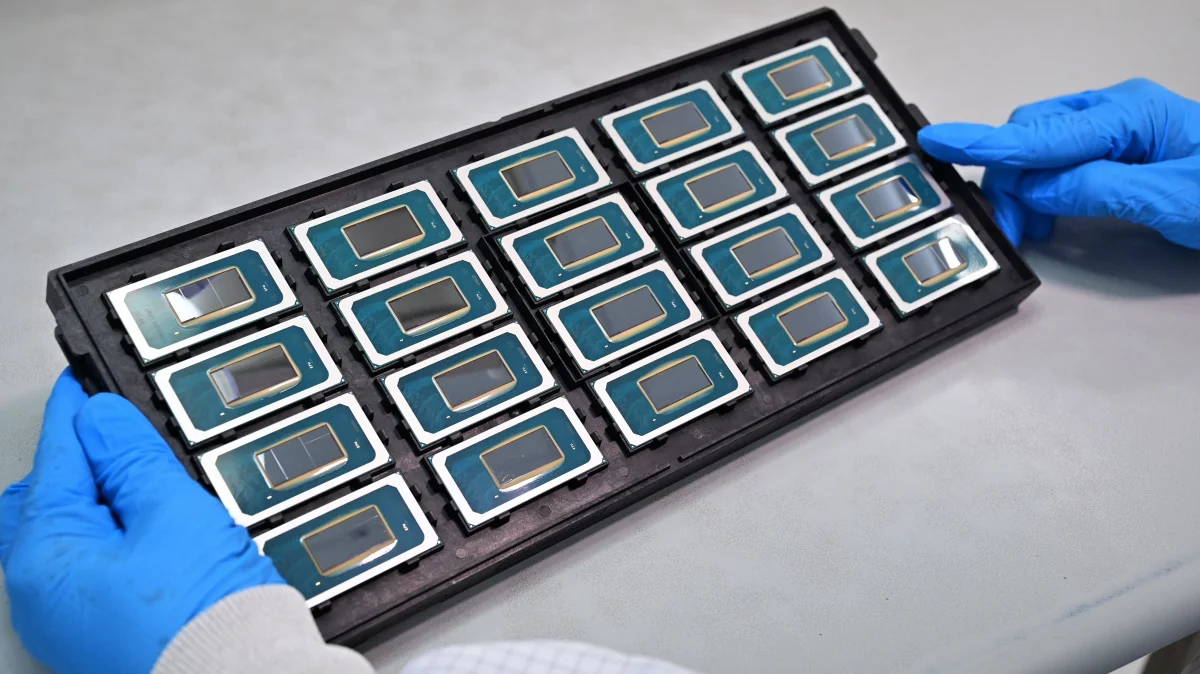




More Stories
Hari pertama Piala Dunia di Singapura dibatalkan karena buruknya udara
Asap mematikan menyelimuti Indonesia – DW – 28 Oktober 2015
Indonesia: Situasi penyandang disabilitas intelektual masih genting